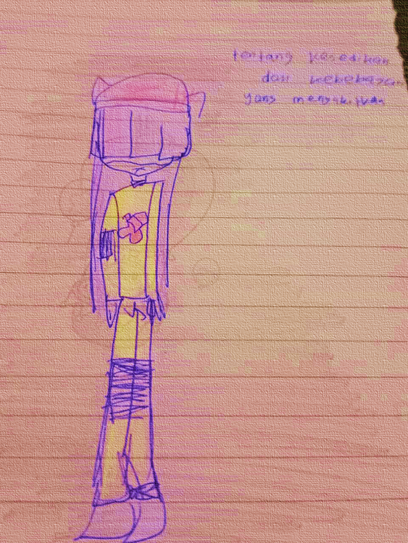Barangkali tak semua luka bisa terucap, tapi izinkan aku memulai dari sini. Beberapa hari terakhir, berita yang terus berdatangan membuatku lelah dan sedih. Mungkin karena aku merasa hidup di negara yang kebijakannya semakin sulit dipahami. Tapi lebih dari itu, mungkin karena aku terus membawa beban sejarah. Sejarah yang hidup dalam cerita keluarga, melekat pada tubuh, dan menjadi luka bersama para perempuan di negeri ini.
Aku lahir di generasi X, generasi yang tumbuh di antara dua dunia: bisikan masa lalu di ruang keluarga dan realitas penuh paradoks hari ini. Almarhum Simbah kakungku adalah saksi masa penjajahan. Ia sering bercerita betapa sulitnya sekadar makan nasi saat itu. Ia tak pernah bersekolah, sehingga paham benar rasanya dibodohi sistem. Karena itu, ketika ibuku lahir, Simbah kakung berjuang keras menyekolahkannya setinggi mungkin. Akhirnya, ibuku menjadi bidan desa, sebuah simbol keberhasilan perjuangan satu generasi perempuan dalam keluarga kami. Ibu pun mewariskan semangat itu padaku: untuk jadi perempuan mandiri dan merdeka. Tapi, bagaimana mungkin merasa merdeka, ketika negara sendiri mengkhianati sejarahnya?
Sejarah mestinya menjadi cermin, agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Tapi akhir-akhir ini, sejarah seolah ditulis ulang oleh mereka yang punya kuasa. Salah satunya soal tragedi 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Seolah kita dipaksa percaya bahwa tak ada yang salah, bahwa tubuh-tubuh yang diperkosa, hilang, dan dibungkam itu cuma bayangan.
Baru-baru ini, anggota DPR Fadli Zon menyatakan tak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Ia juga mengklaim bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.[1] Pernyataan itu bukan hanya menyakitkan ttetapi seperti menampar wajah semua penyintas dan keluarga mereka yang berpuluh tahun membawa trauma.
Ingatanku melayang saat sekolah dulu setiap tahun mendapat tugas untuk membuat ringkasan dari Film G30S/PKI dan yang setia menemani menonton adalah simbah kakung. Aku bertanya “Mbah mengalami zaman PKI enggak?” Simbah hanya menjawab “Jangan ngomong keras-keras soal PKI, nanti ditangkap,” Saat itu aku belum paham benar dan mempercayai bahwa PKI itu musuh negara sebagaimana film yang ku tonton. Setelah dewasa semakin aku membaca dan mendengar dari aktivis perempuan, semakin aku sadar, banyak perempuan jadi korban. Mereka ditangkap, diperkosa, dibunuh tapi suara mereka tak pernah ditulis dalam buku sejarah sekolahku. Pembunuhan terhadap anggota Gerwani, yang diiringi dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, sesungguhnya dapat dikategorisasikan sebagai femisida. Sebab, hal itu adalah pembunuhan berbasis politik seksualitas perempuan.[2] Bahkan hingga kini, rekonsiliasi dan pengakuan negara terhadap femisida 1965 nyaris tak terdengar.
Lalu datang 1998, Sebagai mahasiswa yang masih memiliki energi dan harapan besar pada bangsa ini, kami menorehkan Sejarah untuk perubahan, tetapi di luar sangkaan kita, demonstrasi mahasiswa dibubarkan dengan kekerasan. Orang-orang diculik. Kekacauan meletus. Seperti sejarah sebelumnya, tubuh perempuan kembali menjadi korban.
Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang dialami mencakup kasus pemerkosaan sebanyak 52 korban, pemerkosaan dan penganiayaan berjumlah 14 korban, penyerangan atau penganiayaan seksual mencapai 10 korban, dan pelecehan seksual berjumlah 9 orang. Adapun kasus-kasus tersebut ditemukan di beberapa daerah, termasuk Jakarta, Medan, dan Surabaya. Sedikit berbeda, Tim Relawan untuk Kemanusiaan berhasil mengungkap lebih banyak kasus kekerasan seksual untuk Jakarta dan sekitarnya, yakni lebih dari 150 kasus. Termasuk di antaranya korban-korban yang meninggal.[3] Dari segi intensitas kekerasan terhadap sebagian korban yang menjadi sasaran serangan, dimensi sentimen anti rasial terhadap golongan etnik Cina.[4]
Tapi bukannya mendapat keadilan, para perempuan penyintas justru dibungkam. Banyak dari mereka memilih diam, bukan karena mereka lemah, tapi karena negara tak memberi ruang aman untuk mereka bersuara. Salah satu penyintas yang bersuara adalah Ita Martadinata. Ia tidak hanya membawa trauma, tapi juga membawa keberanian. Ia dijadwalkan menyampaikan kesaksiannya dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun belum sempat ia berdiri di panggung peradilan dunia, nyawanya hilang secara tiba-tiba. Tanpa tahu penyebabnya, tanpa ada keadilan untuknya. Tapi semangatnya tetap hidup. Ia menjadi simbol perlawanan perempuan atas kekerasan sistemik dan usaha membungkam sejarah.
Menolak Lupa, Merawat Luka. Menulis ini mungkin takkan mengubah kebijakan negara. Tapi ini adalah caraku untuk tidak lupa. Untuk tidak diam. Untuk terus menyuarakan bahwa sejarah tak boleh dikaburkan, apalagi oleh mereka yang ingin membungkam kebenaran.
Aku percaya, cerita Simbah Kakung, cerita Ibuku, cerita Ita Martadinata, dan semua perempuan penyintas lainnya harus terus dihidupkan. Agar generasi mendatang belajar sejarah dari kisah keberanian, bukan doktrin ketakutan. Cerita adalah benih keberanian. Jangan biarkan sejarah dibungkam oleh ketakutan.
Penulis: Rose Merry
Campaign Officer YKPI | Pemerhati Isu Perempuan
[1] https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gen0d3qr8o
[2] https://www.konde.co/2024/09/perempuham-femisida-dalam-tragedi-1965-dan-perempuan-bersuara-lewat-dialita-choir/
[3] https://www.kompas.id/artikel/jejak-kekerasan-seksual-dalam-kerusuhan-mei-1998-2